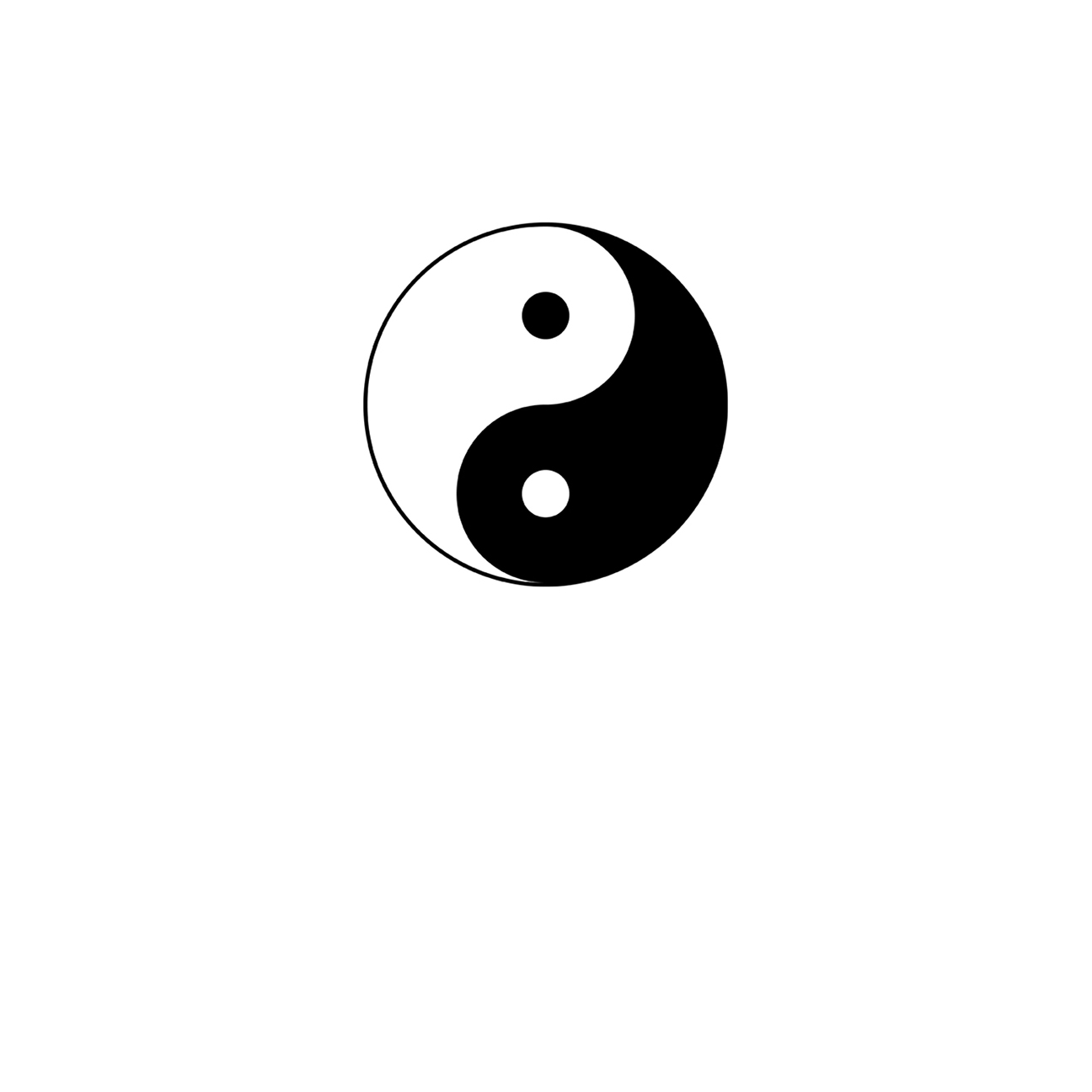In Memoriam
Tan Tjiok Gie (1953–2013)
Saya mengenal Gie di SMP. Ia pindahan dari sekolah lain. Pada awalnya, sebagaimana lazimnya “anak baru”, ada rasa canggung pada dirinya, yang terekspresikan pada sikapnya yang seperti lebih banyak menahan diri. Bisa jadi kecanggungannya itu juga disebabkan oleh beban psikologisnya sebagai adik dari salah seorang guru kami: ibu Tan, walau Gie justru tidak ingin kesan bahwa mentang-mentang ia adalah kerabat guru itu tercermin pada sikap-sikapnya.
Walau berbeda kelas, kami sesekali bertemu pada jam istirahat, sesekali mengobrol, dan segera menjadi akrab. Gie kemudian jadi sering ke rumah saya di jalan Trunojoyo, selalu dengan ditemani motor DKW-nya.
Berbeda dengan teman-teman lainnya, Gie hampir tidak pernah mengajak saya keluar berjalan-jalan dengan motornya (seingat saya hanya satu dua kali ia mengajak saya jalan, itu pun hanya untuk sekadar bermain di rumahnya di daerah Petemon). Di rumah saya, kami biasa melewatkan waktu dengan mengobrol saja hingga malam hari, biasanya yang saya selingi sambil bermain gitar. Dalam banyak kesempatan, Gie lebih sering menempatkan diri sebagai pendengar yang baik.
Kami kemudian harus berpisah—sebagaimana halnya saya juga harus berpisah dengan teman-teman SMA lainnya—pada 1972, ketika saya melanjutkan studi ke Yogya. Sejak itu nyaris tidak ada kontak lagi di antara kami kecuali sesekali ketika saya berkesempatan pulang ke Surabaya dan berkumpul kembali bersamanya, biasanya juga bersama teman-teman lainnya: Hian Swie, Soen Hok, Maritjie, Happy, dll.
Sepanjang berteman dengannya, belum pernah sekali pun saya melihat ia menunjukkan sikap marah, atau menganggap rendah, apalagi sampai mengejek temannya. Gie menyikapi berbagai hal lebih banyak dengan senyum atau tawa.
Sesuatu yang tidak diduga terjadi ketika saya menikah di Yogya (1983). Saya yang tidak begitu suka dengan keramaian sengaja menghindari pesta. Jadi saya tidak mengirimkan undangan ke teman-teman, kecuali sebuah surat pemberitahuan berbentuk puisi mengenai akan berlangsungnya pernikahan kami.
Sungguh mengharukan sekali, ketika saya dan Shirley keluar dari gereja seusai acara pemberkatan pagi itu—di kejauhan, di tengah keramaian para jemaat, tampak Gie melambaikan tangannya ke arah kami, diiringi senyumnya yang khas itu. Ternyata Gie sengaja datang dari Surabaya—walau tidak diundang—hanya untuk menyampaikan selamat kepada kami berdua, dan langsung kembali ke Surabaya sesudahnya! Dalam surat yang saya kirimkan kepadanya itu bahkan tidak ada informasi apa pun mengenai akan diadakannya acara pemberkatan itu, apalagi mengenai waktu dan tempatnya!
Selamat jalan Gie, persahabatan dan senyum tulusmu akan selalu kami kenang.
Hanny Kardinata
Jakarta, 29.08.13