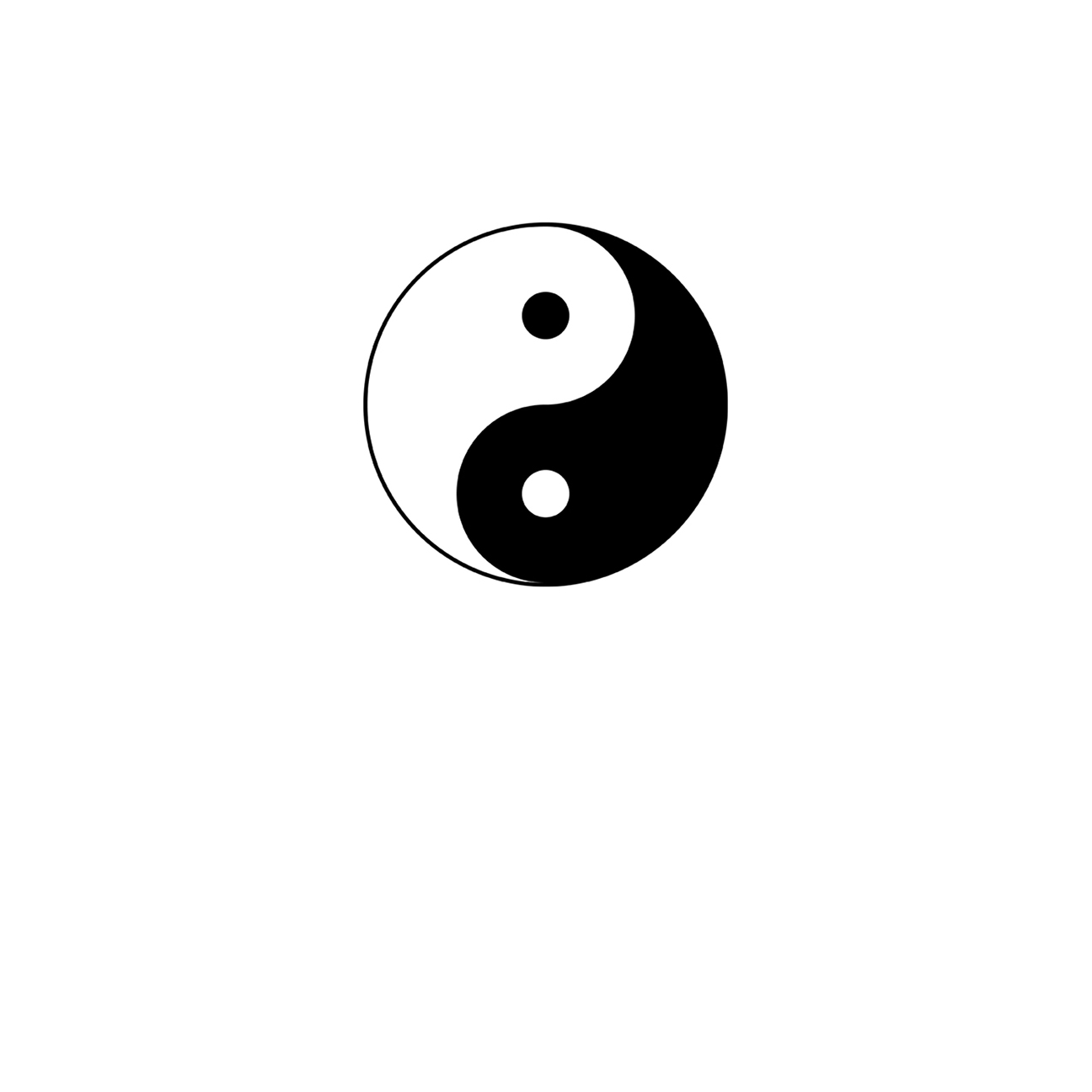Di Indonesia, hingga sekitar tahun 1960/70an, istilah tipografi belumlah begitu dikenal sebagaimana pengertiannya sekarang. Pada masa itu, tugas-tugas di kampus desain masih dikenal dengan nama lettering; mahasiswa harus membuat huruf dengan tangan (hand-drawn lettering), dimana ketrampilan menggunakan kuas dan cat poster (gouache) menjadi batu ujian utama dalam menentukan kualitas sebuah karya. Legibility dan readability menjadi sesuatu yang tidak mudah dicapai mengingat faktor optis yang bisa berubah ketika huruf-huruf masih ‘diset’ dengan pensil dengan ketika sudah diisi dengan warna (filled), apalagi kalau latar belakangnya berwarna pula. Bekerja dengan mengandalkan ketrampilan tangan masih menjadi satu-satunya pilihan teknis saat itu.
Memasuki tahun 1970an, artis-artis di kantor-kantor agensi periklanan di Indonesia sudah mulai menggunakan huruf gosok (instant lettering dry transfer) untuk menset headline iklan, yang paling populer saat itu adalah yang diproduksi oleh Letraset (Inggris), Mecanorma (Perancis) dan belakangan oleh Rugos (Indonesia). Sementara untuk naskah iklan (body copy) diset dengan mesin tik IBM. Baru pada periode berikutnya yaitu pada pertengahan 1970an mesin elektrik ini digantikan oleh mesin phototypesetting yang diproduksi oleh Compugraphic, yaitu mesin setting huruf yang menggunakan proses fotografis (output-nya berupa kertas bromide, kertas foto yang mengandung bahan kimia perak bromida).
Desain grafis termasuk tipografi kemudian mengalami perkembangannya yang paling revolusioner ketika komputer Macintosh mulai dikenal di Indonesia semenjak paruh kedua tahun 1980an. Proses pekerjaan yang sebelumnya dilakukan dengan sistem manual diambil alih sepenuhnya oleh komputer. Tangan digantikan oleh pixel, free hand oleh vector. Komputer menjanjikan kemudahan-kemudahan yang tak terbayangkan sebelumnya, dan menjelang pergantian milenium, semakin banyak saja desainer grafis yang menjadi semakin bergantung pada komputer.
Tetapi di Amerika, memasuki dekade pertama tahun 2000an, di tengah eforia penggunaan komputer, hand-drawn lettering justru populer kembali. Gejalanya sudah terlihat beberapa tahun sebelumnya ketika grunge typography menjadi begitu populer (termasuk juga di Indonesia) antara lain melalui David Carson (disebut-sebut sebagai “The Father of Grunge Design“) yang menggunakan tipografi sebagai medium untuk berekspresi. Steven Heller bahkan menyebut dasawarsa pertama tahun 2000 ini sebagai “The Decade of Dirty Design“, suatu dekade dimana generasi baru desainer grafis berpaling kembali ke penggunaan tangan (to get back to the hand): “Mastery of the computer’s options meant that by the end of the 20th century a new generation of designers were commanding much more than merely Illustrator, Quark and Photoshop programs—they had figured out how to wed technique to concept, and produce design that often had an exterior life other than the client’s message.“ Maka terbentanglah kini pilihan-pilihan teknis dalam berkarya, sepenuhnya memakai komputer (digital), atau menggunakan tangan saja (anti-digital) atau menggunakan kedua-duanya secara bersamaan.
Dan dibandingkan dengan masa di mana hand-drawn lettering masih merupakan satu-satunya pilihan, di depan mata kini tersedia ratusan ribu jenis fonts untuk dipilih dan dipakai, suatu ‘kemudahan’ yang sungguh bisa menyulitkan. Desainer masa kini pun dituntut untuk pandai-pandai menentukan pilihannya, yang ditengarai oleh Heller sebagai “a critically exciting time to be a graphic designer”.
Buku “Tipografi” buah karya Surianto Rustan ini diharapkan akan membantu desainer-desainer Indonesia masa kini untuk memilih dan menggunakan font dengan baik dan benar, serta sukses menghadirkan message yang diusungnya secara estetis. Surianto Rustan, dengan ketekunan dan kerja kerasnya, telah melahirkan sebuah buku yang komprehensif mengenai tipografi, sejak dari awal sejarahnya, mengenal anatomi huruf, mengidentifikasinya, hingga memilih dan kemudian mengeksplorasinya.
Dengan rasa syukur saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku “Tipografi”, semoga bermanfaat bagi perkembangan desain grafis Indonesia umumnya dan tipografi khususnya.
Hanny Kardinata
Founder DGI (Desain Grafis Indonesia)
http://www.DGI-Indonesia.com
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artikel terkait: Buku Baru Karya Surianto Rustan: “Hurufontipografi”
•••