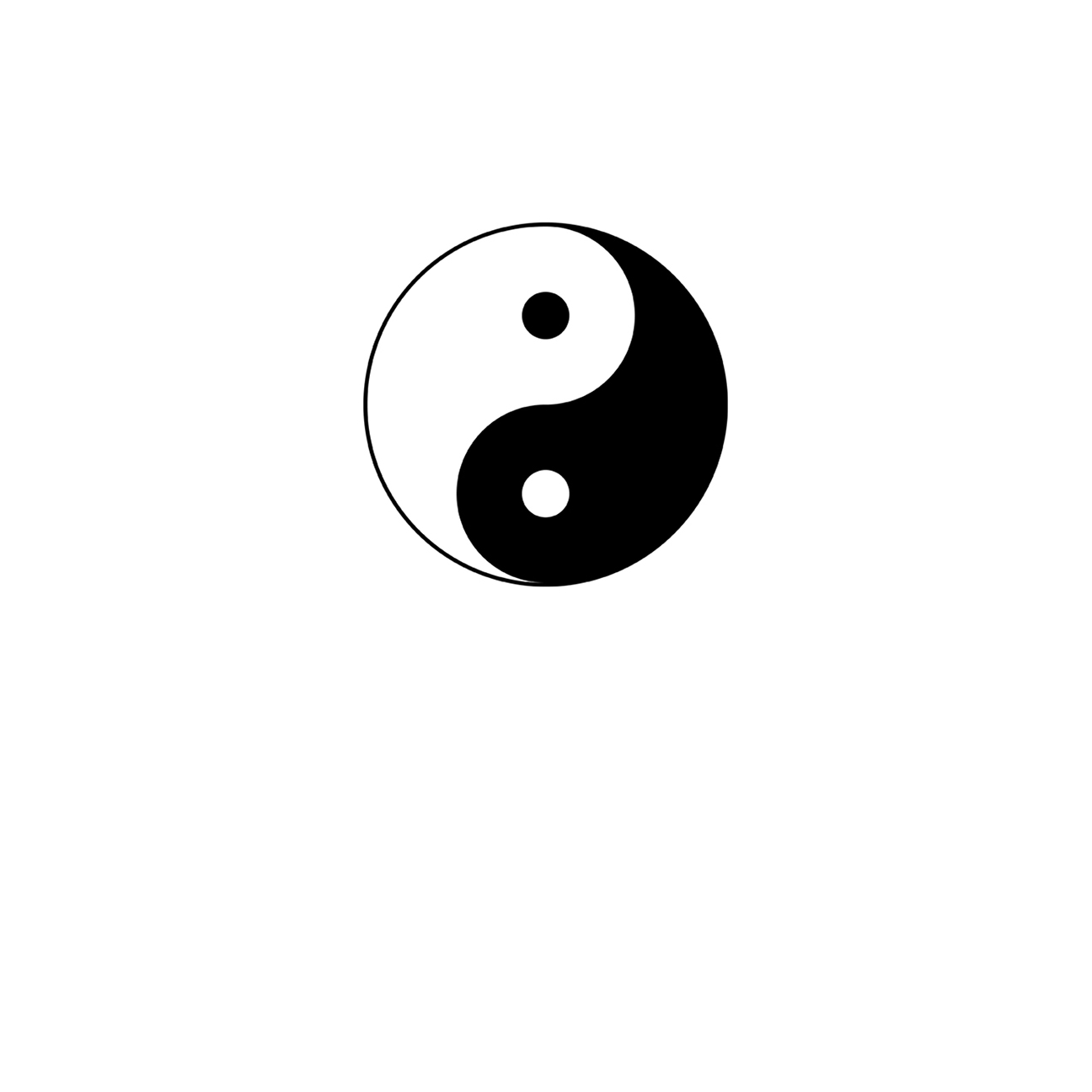Apa yang anda bayangkan jika mendengar kabar akan diselenggarakan sebuah kompetisi atau ajang penghargaan? Sebuah adu kemampuan untuk mencapai yang tertinggi, terkuat, tercepat atau apa pun, sebagaimana yang biasa kita saksikan di layar kaca atau baca di media-media on-line dan tercetak?
Lalu bagaimana seandainya ada kompetisi yang sebaliknya, juaranya justru adalah yang terendah?
Inilah rupanya yang akan dinyatakan oleh IGDA (Indonesian Graphic Design Award), sebuah wujud penghargaan bermartabat bagi desainer grafis Indonesia yang baru pertamakalinya akan diadakan di Indonesia.
Lho kenapa bermartabat kalau pengakuan diberikan hanya kepada yang paling rendah?
Indonesia memiliki semangat luhur warisan leluhur mengenai superiotas – bertolakbelakang dengan apa yang diyakini oleh dunia Barat – yang dinyatakan melalui simbolisasi “bagai padi yang makin berisi makin merunduk” yang bermakna semakin tinggi pencapaian seseorang semakin rendahlah hatinya.
Bagi petani, kata-kata ini tidak berhenti hanya sebatas bibir, tapi telah menjadi kearifan hidup mereka turun temurun. Dengan kata lain, dari sekedar varietas yang ditanam untuk dimakan, padi –semenjak ditanam sampai dipanen– hadir sebagai suatu ritual yang menghidupi jiwa masyarakat penanamnya.
Analog dengan siklus padi itu, para petani grafis juga menjalani siklus berkarya sejak menanam (ide), bertumbuh dan merunduk (proses) hingga memanen (output). Dan rupanya, IGDA melihat “padi yang merunduk” itu sebagai gambaran idealisasi seorang juara, yang tetap rendah hati, bertanggungjawab dan lebih banyak memberi daripada menerima.
Selanjutnya kalau di abad ke-10 –menurut catatan Jonathan Rigg, ahli geografi dari University of Durham– Indonesia telah menjadi eksportir beras, maka mengapa tidak bila petani grafis masa kini mencoba mengulang hal yang sama, dengan berupaya mengekspor karya-karyanya supaya ikut mewarnai desain grafis dunia, sejajar tapi dengan gayanya sendiri?
Inilah idealisasi kedua yang rupanya diemban oleh IGDA sehingga bertekad memberikan apresiasi khusus bagi karya desain yang menghidupkan kembali atau yang melakukan inovasi terhadap inti-inti kebudayaan lokal. IGDA, lebih dari sekedar ajang penghargaan dan kompetisi pada umumnya, sesungguhnya menjadi cermin para petani grafis untuk berintrospeksi kembali membumi dan memberi kehidupan kembali kepada desain lokal.
Lalu sedemikian pentingkah bagi IGDA untuk memberi penghargaan khusus bagi karya desain masa kini yang mampu mempromosikan konsep desain lokal?
Telah terbukti memang bahwa yang mampu bertahan dari serbuan pasar global adalah petani grafis yang mampu merevitalisasi desain lokal untuk bersaing dan memiliki karakter di dunia internasional.
Mengenai hal ini pernah diungkapkan oleh Ray Bachtiar Drajat, fotografer yang sangat mendambakan identitas keIndonesiaan, dalam bukunya “Ritual Fotografi”, bahwa:
“Contoh kasus yang bisa dihubungkan dengan pentingnya budaya lokal dimunculkan ke permukaan adalah “gesekan” dengan negara tetangga kita, Malaysia. Sepertinya Pemerintah Negeri Jiran sudah menyadari betul bahwa dalam hal perdagangan harus ada “brand image” yang dijual selain kompromi dengan selera pasar. Nah, membaca kecenderungan ini, mungkin Malaysia yang sudah sadar akan pentingnya brand image ini sedang membidik pasar masyarakat internasional, lalu dengan sadar menjual budaya lokal dalam hal ini industri “batik” yang mereka akui sebagai industri batik tradisi Malaysia yang berkelanjutan (padahal kita tahu bahwa budaya batik adalah budaya Jawa). Dan bukan itu saja, dengan tak merasa berdosa sedikit pun, hampir seluruh kesenian dan budaya Indonesia kini dipublikasikan Malaysia dengan alasan “masih serumpun”.”
“Tentang perlu tidaknya konsep lokal kita angkat untuk bisa muncul di dunia digital yang tujuan utamanya adalah global, jelas perlu kita pertimbangkan lagi. Apalagi jika mengingat teori Malaysia, yang menjelaskan betapa pentingnya sebuah ciri yang bisa cepat mengingatkan pasar akan “siapa aku”. Contoh lokalitas yang bisa bersaing di pasar global adalah Jepang. Di bidang animasi Jepang yang teknologi awalnya mengacu pada teknologi animasi global seperti animasi-animasi produksi Walt Disney, kini malah menjadi trenseter. Ke-lokal-an konsep animasi Jepang bahkan menjadi inspirasi dan acuan sutradara-sutradara muda Hollywood seperti Wachowski bersaudara yang melahirkan trilogi sinema “The Matrix”.“
Dan sebagai penutup, saya kutipkan apa yang pernah disampaikan oleh Sultan Hamengku Buwono X melalui orasi budayanya pada pembukaan pameran Biennale Jogja IX tahun 2007:
“Oleh sebab itu, kita sendiri jangan kalah oleh Malaysia dalam mengembangkan semangat kebangsaan, dengan menjadikan pluralisme perekatnya, sebagai ketahanan bangsa yang ampuh dalam menghadapi pergulatan globalisasi. Kita juga harus menjaga dan memelihara, serta merevitalisasi dan mengembangkan khasanah pusaka budaya kita yang memang amat kaya ini. Jangan sampai terjadi bangsa lain yang mengaku memiliki warisan budaya-budaya Nusantara, hanya karena mereka yang mampu mengembangkannya ke tingkat dunia.”
Jadi, mengapa tidak?
Ditulis oleh Hanny Kardinata berdasarkan masukan dari Henricus Kusbiantoro dan Ray Bachtiar Drajat.
jakarta, 13 Mei 2009
•••